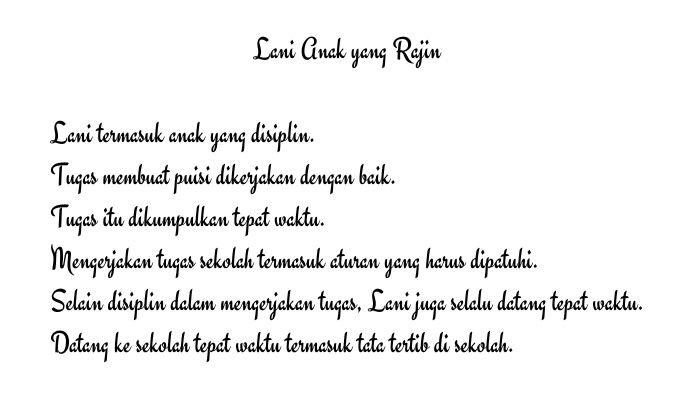Oleh Hendriyatmoko
Guru SMK Muda Cepu dan Anggota Satupena Kabupaten Blora
Malam itu, kota kecil di kaki gunung Merbabu baru saja tersapu hujan deras. Rintiknya belum sepenuhnya reda ketika Arman berdiri di teras rumah, menatap lekat ke jalan setapak yang mengarah ke rumah Chika. Hatinya masih berdebar mengingat kejadian beberapa jam lalu.
Padahal, jika malam itu tak terjadi hujan, segalanya mungkin berbeda.
Sore harinya, langit masih cerah. Arman, Joko, Agus, Darto, dan Wahyu sedang nongkrong di warung bu Sari, membahas rencana pentas seni kampung. Arman sebenarnya tak ingin lama-lama di situ. Ia sudah berjanji akan bertemu Chika di taman kecil belakang balai desa, tempat mereka biasa bertukar cerita.
“Bro, bentar lagi hujan. Awan barat gelap banget,” ujar Wahyu sambil menunjuk ke langit.
Arman hanya tersenyum. “Aku cuma mau sebentar. Chika udah nunggu.”
Joko bersuit pelan. “Cieee, pacaran diam-diam ya?”
Arman menggeleng. “Bukan pacaran. Cuma… ngobrol aja.”
Namun semua tahu, Arman dan Chika saling menaruh rasa. Mereka hanya terlalu takut pada perbedaan yang membentang — bukan hanya karena keluarga, tapi juga masa lalu. Keluarga Arman pernah berselisih dengan keluarga Chika soal batas tanah warisan. Sejak saat itu, hubungan dua keluarga itu dingin seperti salju.
Saat Arman sampai di taman, hujan mulai turun rintik. Tapi Chika sudah di sana, duduk di bangku kayu basah, mengenakan sweater abu-abu dan menunduk.
“Maaf telat. Aku—” Arman menghentikan kalimatnya saat melihat wajah Chika murung.
“Kita gak bisa terus begini, Man,” ucap Chika pelan.
Arman menarik napas. “Kenapa? Karena orang tuamu?”
Chika diam sejenak. “Bukan cuma itu. Ibuku sakit. Ayahku keras kepala. Kalau mereka tahu aku sering ketemu kamu, aku takut…”
Petir menyambar di kejauhan. Arman duduk di sampingnya, walau hujan makin deras.
“Chik, aku serius. Aku sayang kamu. Kita gak harus sembunyi terus. Aku akan bicara dengan Bapak dan Ibu.”
Chika menatapnya dengan mata berkaca. “Kamu yakin? Ayahmu—”
“Aku yang akan urus semuanya. Kalau malam ini aku gak ngomong ke mereka, aku pengecut.”
Dan malam itu, basah kuyup oleh hujan, Arman pulang. Ia mengetuk pintu ruang tengah, mendapati Wiryo sedang membaca koran dan Wati menyiapkan teh.
“Aku mau bicara, Pak. Bu. Tentang Chika.”
Pertengkaran terjadi malam itu. Wiryo meledak. “Kamu waras, Man? Kamu tahu siapa ayahnya? Karyo itu manusia keras kepala, yang pernah mau gebuk aku cuma gara-gara batas tanah!”
Wati mencoba menengahi, tapi suara Wiryo mengalahkan semuanya.
Namun, malam itu juga, karena derasnya hujan yang memaksa semua diam di rumah, Arman bicara dari hati ke hati. Ia tak pergi. Ia bertahan di ruang tengah, meski suaranya gemetar, meski wajah ayahnya merah.
Esok harinya, kabar pertemuan Arman dan Chika sampai juga ke telinga Karyo. Karti sempat menjerit, Dita dan Salsa mencoba menenangkan.
Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi.
Dewi, tetangga mereka, datang membawa kabar: “Pak Wiryo kirim salam. Katanya ingin bicara baik-baik. Katanya, Arman yang minta.”
Jika malam itu tak terjadi hujan, mungkin Arman tak akan pulang cepat.
Jika malam itu tak terjadi hujan, mungkin ia tak akan punya keberanian bicara dengan orang tuanya.
Dan jika malam itu tak terjadi hujan, mungkin cinta mereka tetap diam-diam di bangku taman, di antara rintik yang menyembunyikan ketakutan mereka.
Tapi karena malam itu hujan turun deras, dua keluarga yang dulu bertikai mulai membuka jendela bicara. Karena malam itu, Chika dan Arman tidak berpisah. Dan karena malam itu pula, cinta yang tertahan akhirnya punya jalan.